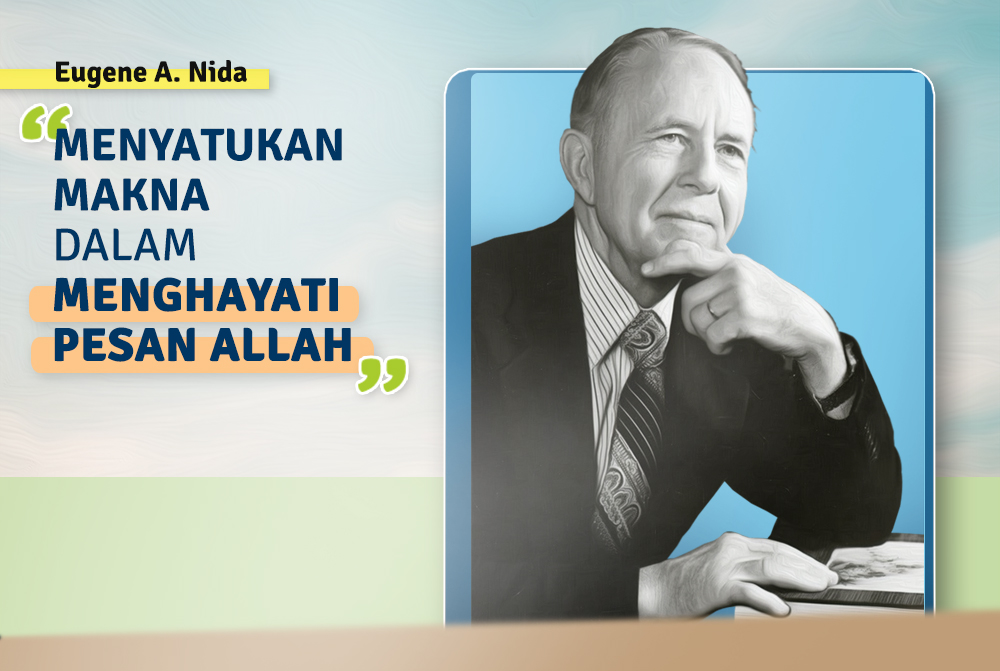Oleh Sigit Triyono
"Lojor henteu beunang dipotong, pendek henteu beunang disambung" (panjang tidak boleh dipotong dan pendek tidak boleh disambung). Itulah filosofi masyarakat Badui dalam menjaga melestarikan kawasan hutan lindung.
Dalam penghayatan saya, filosofi di atas bisa diringkas hanya dalam dua kata: "jangan rakus". Dan bukan hanya berlaku untuk menjaga hutan, tetapi diterapkan dalam hidup secara keseluruhan.
"Benar begitu ya Kang Yayat?," tanya saya kepada si tuan rumah dimana saya dan rombongan menginap satu malam di kampung Badui Luar.
Kang Yayat mengangguk dan berkata kalem: "iya benar."
Untuk menuju ke kediaman Kang Yayat di kampung Gajebo, desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, tidaklah mudah. Perjalanan dari Jakarta membutuhkan waktu hampir seharian menggunakan kereta api, mobil, serta berjalan kaki.
Saya dan rombongan backpackers (empatbelas orang) berangkat dari stasiun kereta Tanah Abang pada Sabtu pagi, 4 Juni 2023 pukul 7.30 WIB. Hampir dua jam barulah kami sampai di stasiun Rangkasbitung.
Karena kami ingin melihat "Jembatan Akar" sebelum masuk ke kampung Badui, maka kami mampir sekira satu jam di desa Cijahe. Sesudah perjalanan dengan mobil Elf berkapasitas 15 orang selama satu jam dari stasiun Rangkasbitung.
Untuk menuju ke lokasi "Jembatan Akar" kami harus berjalan kaki menelusuri sawah, menanjak bukit, dan menurun ke arah sungai Cisemet dengan total berjalan sekira 30 menit.
Setelah menikmati Jembatan Akar yang pernah viral, kami kembali berjalan kaki menanjak dan menurun ke tempat parkir mobil. Rasa dahaga di tengah terik matahari sungguh terobati dengan air kelapa muda yang dijual penduduk di tengah perjalanan.
Jembatan Akar memang unik. Jembatan yang merupakan penggabungan akar-akar dua pohon sangat besar di dua sisi sungai Cisemet. Lebar sungai kurang lebih 30 meter. Jembatan Akar sangat menolong banyak orang untuk menyeberangi sungai yang cukup dalam dan menghubungkan desa Panyelarangan dan Nungkulan. Tentulah puluhan tahun proses akar-akar ini bisa nyambung dan akhirnya menjadi jembatan penyeberangan.
Di kawasan desa Badui tidak boleh ada kendaraan, meski hanya sepeda motor. Kemanapun pergi dari kampung ke kampung, orang Badui memilih untuk berjalan kaki. Benar-benar merupakan ekspresi dari kalimat di awal tulisan ini.
Sesudah istirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan ke tugu Selamat Datang Badui di desa Ciboleger. Perjalanan berlanjut selama sekitar 30 menit dengan mobil Elf yang setia menunggu kami.
Jam menunjukkan pukul 16.00 WIB dan kami memasuki pintu gerbang menuju perkampungan Badui. Ada empat kampung yang semuanya akan kami lewati dan kami menginap di kampung paling jauh, kampung yang kelima, yaitu kampung Gajebo.
Menurut keterangan penduduk setempat, kami harus berjalan kaki sekira satu jam. Padahal menurut peta jaraknya hanya 2.4 Km. Ternyata bukan jaraknya yang jauh, tetapi naik-turun bukit terjal dan jalan berbatuan yang menguras tenaga, sehingga akhirnya harus ditempuh lebih dari satu jam berjalan kaki.
Akhirnya kami sampai di kampung Gajebo sekira pukul 17.30 wib, tetapi suasananya serba gelap. Tidak ada listrik mengalir ke kampung karena penduduk menolak adanya listrik dari pemerintah. Suasana alami dan damai sangat terasa. Untunglah ada sinar rembulan yang semakin malam terasa semakin kuat terangnya melingkupi semesta.
Tidak ada televisi, tidak ada internet, tidak ada suara bising, yang ada hanya suasana damai bersama alam dengan suara jangkrik dan kadang gonggongan anjing kampung.
Kang Yayat adalah sosok mantan penduduk Badui Dalam yang berpindah ke Badui Luar sejak delapan tahun lalu. Dia menikah dengan Sani yang juga berasal dari Badui Dalam dan memiliki anak lelaki berusia lima tahun bernama Satria.
Melalui Kang Yayat ini saya dan kawan-kawan mendapatkan informasi tentang tradisi orang Badui. "Mengapa anak-anak Badui tidak boleh sekolah?" tanya saya kepadanya. "Memang aturannya begitu Pak. Para tetua kami melarang anak-anak masuk sekolah.," kata Kang Yayat. "Tapi Kang Yayat dan juga Kaldi (saudaranya) bisa baca tulis hitung dan bahkan ber WA pakai HP?," tanya saya penasaran.
Kang Yayat berkisah, meski di kampung Badui (baik luar maupun dalam) tidak boleh ada sekolah formal, tapi anak-anak belajar dari pergaulan dengan masyarakat di luar Badui. Interaksi dengan masyarakat luar memang semakin intens. Apalagi kunjungan wisatawan semakin banyak dan transaksi perdagangan semakin intens.
Pakaian adat pria orang Badui Luar adalah celana pendek dan baju hitam serta ikat kepala biru bermotif batik. Dalam keseharian sudah banyak yang memakai celana pendek jins dan T-shirt. Namun tetap kemana-mana menyelipkan golok ukuran sedang sebagai alat kerja sekaligus aksesori pria.
Perempuannya mengenakan kain kebaya hitam dan bawahannya kain batik biru yang sama dengan ikat kepala para pria Badui. Dalam keseharian para perempuannya tampak lebih banyak yang mengenakan pakaian adatnya.
Pada Minggu 5 Juni lalu akan ada acara hajatan pernikahan orang Badui di kampung Gajebo. Ada lebih dari seratus ibu-ibu berpakaian adat dan membawa berbagai makanan menuju ke rumah Kang Yayat serta beberapa rumah sebelahnya. Mereka akan menumbuk padi bersama di dekat lumbung desa dan akan memasak bersama untuk keperluan hajatan.
Nilai-nilai gotong royong sangat kuat terasa. Sementara para perempuan menumbuk padi, para bapak mendirikan sebuah bedeng (rumah bambu) untuk tempat memasak yang akan disajikan dalam hajatan.
Di tengah gelombang globalisasi dan digitalisasi di berbagai segi kehidupan, Kang Yayat dan sesama suku Badui Luar masih mempertahankan nilai-nilai luhur: hidup sederhana, anti rakus, dan serba secukupnya.
Keugaharian sungguh nyata. Saya mendapatkannya bukan dari kotbah atau ceramah, tetapi dari praktik hidup saudara-saudara kita yang tinggal di desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang berjarak sekira 160 km dari Jakarta. (ST.6.6.2023)