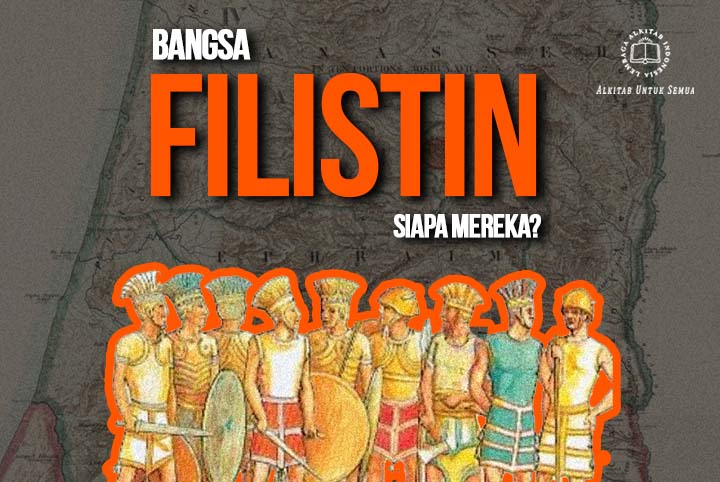Anak-anak dalam masyarakat kerap kali diposisikan sebagai individu yang belum utuh, sekadar miniatur orang dewasa, atau bahkan sebagai objek pasif dalam ruang sosial dan keagamaan. Dalam konteks Indonesia, laporan tahun 2024 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa 50,7% anak mengalami kekerasan, baik secara verbal, emosional, fisik, maupun pengabaian. Dalam situasi ini, gereja dan umat Kristiani dipanggil untuk menjadi suara profetik yang tidak hanya mengadvokasi hak-hak anak, tetapi juga mengembangkan pemahaman iman yang memanusiakan anak secara utuh.
Perspektif Alkitab tentang Anak
Gambaran Positif: Anak sebagai Teladan Iman Alkitab menghadirkan berbagai narasi yang menempatkan anak sebagai subjek penting dalam rencana Allah. Dalam Markus 10:13–16, Yesus menegaskan pentingnya menyambut anak-anak dan bahkan menempatkan mereka sebagai model penerimaan terhadap Kerajaan Allah, “Siapa saja yang tidak menyambut Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.” Tindakan Yesus yang memeluk dan memberkati anak-anak (Markus. 10:16), menunjukkan dimensi spiritual dan sosial dari penerimaan dan penghargaan terhadap anak. Pesan ini menjadi fondasi kuat untuk membangun teologi yang ramah anak.
Gambaran Problematis: Ayat-Ayat Kekerasan dan Pengabaian
Meskipun ada teks-teks yang mengangkat harkat anak, tidak sedikit pula teks yang menyisakan persoalan etis. Amsal 13:24, misalnya, berbunyi: “Siapa tidak menggunakan tongkat, membenci anaknya; tetapi siapa mengasih anaknya, menghajar dia pada waktunya.” Dalam versi BIMK, teks ini bahkan lebih eksplisit, “Tidak memukul anak berarti tidak cinta kepadanya; kalau cinta, harus berani memukul dia.” Teks ini sering digunakan sebagai legitimasi untuk kekerasan dalam pendidikan anak. Namun, pembacaan kontekstual dan historis membuka ruang tafsir alternatif. Kata "tongkat" dalam budaya penggembalaan bisa dipahami sebagai alat pengarahan, bukan pemukul. Tongkat gembala digunakan untuk melindungi, mengarahkan agar domba domba tidak berjalan di tempat bahaya, bukan menyakiti. Demikian pula kata Ibrani סרָ וּמ (musar), yang diterjemahkan sebagai “menghajar", dalam ayat lain juga berarti “didikan” (lihat Amsal 1:8; 3:11). Tafsir semacam ini menjadi upaya hermeneutis untuk menyelamatkan makna teks dari penyalahgunaan dan menjadi jembatan bagi pembacaan yang ramah anak.
Selain itu, narasi seperti kisah Hagar dan Ismael (Kejadian 21:14–16) atau Musa yang diletakkan di sungai (Keluaran 2:1–10) juga menampilkan dimensi pengabaian dari perspektif anak. Meskipun secara naratif tindakan itu dimaknai sebagai penyelamatan, pendekatan teologis yang mempertimbangkan perspektif anak memungkinkan kita membaca ulang teks dengan kesadaran akan pengalaman trauma dan ketidakberdayaan anak dalam situasi krisis.
Teologi Ramah Anak: Membangun dari Narasi dan Pengalaman Anak sebagai Subjek Teologis
Teologi ramah anak mengusulkan paradigma baru yang melihat anak bukan hanya sebagai objek pengajaran, tetapi sebagai subjek yang memiliki kapasitas spiritual dan interpretatif. Konsep “teologi cilik” sebagaimana disebut oleh Pdt. Justitia Vox Dei Hattu, Th.D., pakar pendidikan Kristiani, memperkenalkan pendekatan di mana anak-anak menafsirkan pengalaman iman mereka secara mandiri dan bermakna. Dalam hal ini, suara dan pertanyaan anak harus dihargai sebagai bagian dari diskursus teologi yang sah. Contoh dapat dilihat dari pertanyaan anak, misalnya tentang salib Kristus yang penuh darah dan penderitaan, “Kenapa Tuhan yang mengasihi kita justru mati dengan cara sekejam itu?” Pertanyaan semacam ini menantang orang dewasa untuk keluar dari bahasa teologis yang abstrak dan mengembangkan narasi iman yang lebih empatik, naratif, dan sesuai perkembangan kognitif anak.
Banyak media pembelajaran iman, terutama dalam konteks gereja, masih menggunakan pendekatan visual yang tidak ramah anak. Visualisasi penyaliban, misalnya, dapat menimbulkan ketakutan, bukan pemahaman. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi naratif iman yang tidak menampilkan kekerasan sebagai sentralitas, melainkan cinta, pengorbanan, dan relasi. Penggunaan cerita kreatif, gambar penuh kasih, atau pendekatan partisipatif menjadi kunci.
Ecclesia Domestika: Rumah sebagai Ruang Sakral Iman Anak
Konsep Ecclesia Domestika menekankan bahwa rumah adalah tempat pertama dan utama bagi pertumbuhan iman anak. Ini bukan hanya tugas orang tua sebagai guru agama, tetapi lebih sebagai teladan iman dan kasih. Pdt. Jeniffer Fresy Porielly Pelupessy-Wowor, Ph.D., menekankan bahwa perkembangan iman anak berkaitan erat dengan rasa percaya kepada orang di sekitarnya. Ketika lingkungan rumah menciptakan rasa aman, maka relasi dengan Allah pun dapat bertumbuh sehat. Dalam konteks ini, teologi ramah anak juga menyangkut spiritualitas pengasuhan, di mana orang dewasa menyadari bahwa tindakan mereka menciptakan gambaran tentang Allah di benak anak.
Tantangan dan Tanggung Jawab Gereja
Gereja yang Hidup adalah Gereja yang Ramah Anak
Seringkali kehadiran anak dalam ruang ibadah dianggap sebagai gangguan. Padahal, keberadaan mereka justru menandakan regenerasi dan kehidupan dalam tubuh Kristus. Gereja harus membuka ruang untuk partisipasi anak dalam ibadah, bukan hanya di sekolah minggu, tetapi juga dalam bentuk liturgi intergenerasional yang inklusif. Gereja juga harus menjadi tempat aman, terutama di tengah realitas kekerasan terhadap anak. Jika rumah gagal menjadi tempat perlindungan, gereja harus mengambil peran profetik dan pastoral untuk menjadi komunitas penyembuh dan pendamping.
Hermeneutika Ramah Anak sebagai Tanggung Jawab Etis
Membaca Alkitab dari perspektif anak bukanlah sekadar metode tafsir alternatif, tetapi tindakan etis dan profetik. Gereja tidak boleh menggunakan teks sebagai pembenaran kekerasan, melainkan sebagai jalan pembebasan. Hermeneutika ramah anak mengajarkan bahwa semua pembacaan Alkitab harus mempertimbangkan pengalaman anak, dampak psikologis dan spiritual mereka, serta konteks sosial mereka sebagai kelompok rentan. Teologi ramah anak mengajak kita untuk meninjau ulang paradigma teologis, praksis gereja, dan relasi sosial kita dengan anak-anak. Alkitab, meskipun lahir dalam budaya patriarkal dan kerap menghadirkan teks yang problematis, juga menawarkan gambaran yang kuat tentang penerimaan, penghargaan, dan cinta kepada anak-anak. Melalui pembacaan kritis dan kreatif, kita dipanggil untuk membangun teologi yang tidak hanya berbicara tentang anak,
tetapi bersama anak. Anak bukan sekadar objek pembentukan iman, tetapi sahabat spiritual yang memperkaya dan menantang iman kita sendiri.
Dalam dunia yang keras terhadap anak-anak, teologi ramah anak bukan pilihan, melainkan keniscayaan. Sebab di sanalah kita belajar bahwa Kerajaan Allah bukan milik orang dewasa yang kuat, tetapi mereka yang belajar menjadi kecil, percaya, dan tulus seperti anak-anak. Sudahkah gereja Anda menjadi ruang yang aman, ramah, dan membebaskan bagi anak-anak untuk bertumbuh dalam iman?