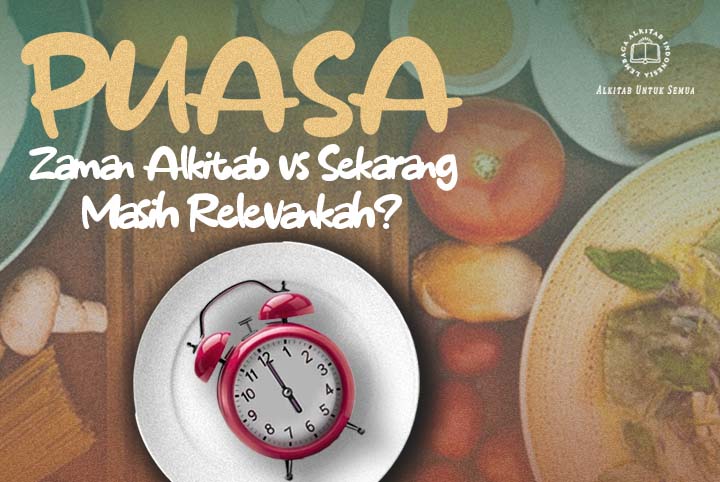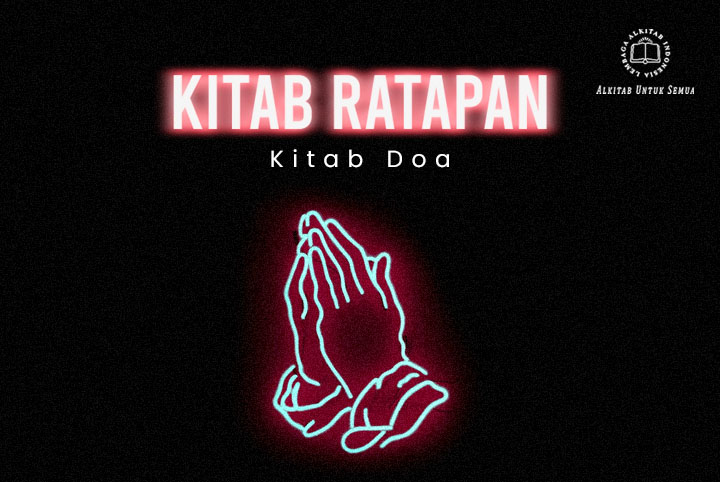Di balik hiruk-pikuk Batavia abad ke-17, seorang pria berdiri di antara arus sejarah, menentang sistem yang menindas. Cornelis Chastelein, pada hari ini mungkin hanya sedikit orang yang masih mengingat namanya. Sebagai karyawan VOC, ia bukan sekadar pedagang yang mengejar keuntungan; ia adalah seorang visioner yang melihat manusia bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai jiwa yang harus dihormati. Bagi kaum mardijkers (keturunan budak Hindia Belanda yang sudah dibebaskan) di Depok, Chastelein dikenal sebagai seorang Protestan sejati. Pandangan dan sikap hidupnya banyak bertumpu pada prinsip cinta kasih sesama manusia. Ia sendiri punya semboyan “Er is geen leven zonder liefde” atau “tiada kehidupan tanpa kasih sayang”.
Di dunia yang masih terjebak dalam rantai perbudakan, Chastelein memilih untuk membebaskan budak-budaknya, memberikan mereka harapan baru di tanah yang ia bangun sebagai komunitas percontohan. Tidak hanya itu, jauh sebelum isu lingkungan menjadi perhatian global, ia telah menanamkan gagasan tentang hutan kota sebagai benteng melawan eksploitasi atas alam. Sosoknya bagaikan jejak cahaya di tengah kelamnya zaman.
Kelahirannya
Amsterdam, Agustus 1657. Di sebuah rumah yang berdiri kokoh di tepi Sungai Rokin, lahirlah seorang anak yang kelak mengguncang sistem yang sudah mapan. Cornelis Chastelein, putra dari Anthoine Chasteleine dan Maria Cruydenier, tumbuh dalam lingkungan yang keras dan penuh intrik. Ayahnya, seorang saudagar besar yang meraup kekayaan dari garam dan anggur, terpaksa meninggalkan Nantes,Prancis akibat kecemburuan pedagang lokal. Amsterdam menjadi pelabuhan baru bagi keluarga ini. Dan kepindahan ke Amsterdan bagai mempersiapkan jalan yang lebih besar bagi Cornelis Chastelein di masa depan.
Cornelis Chastelein memulai perjalanannya ke Hindia Belanda pada usia 17 tahun bersama keluarganya dengan harapan membangun masa depan yang lebih baik. Setelah tiba di Batavia pada 16 Agustus 1675, ia segera bekerja di De Heeren Zeventien sebagai pemegang buku VOC. Keterampilannya dalam mencatat transaksi keuangan membuatnya cepat naik pangkat, dari pemegang buku menjadi pembantu saudagar. Dalam 16 tahun, ia mencapai posisi saudagar tingkat dua, sebuah jenjang karier yang cukup bergengsi dalam perusahaan dagang raksasa tersebut. Namun, yang membedakannya dari pejabat VOC lain bukan hanya kenaikan pangkatnya, melainkan cara berpikirnya yang lebih maju dan humanis.
Keluar dari VOC
Di saat pejabat VOC lain fokus pada eksploitasi ekonomi, Chastelein justru memikirkan dampak jangka panjang dari kolonisasi. Ia menentang kebijakan monopoli perdagangan yang diterapkan VOC dan mengusulkan sistem yang lebih berkelanjutan. Sikapnya ini bertentangan dengan kebijakan Gubernur Jenderal Willem van Outhoorn yang lebih mengutamakan keuntungan instan bagi Belanda. Akibat perbedaan pandangan ini, Chastelein perlahan mengundurkan diri dari jabatannya pada usia 34 tahun. Pada masa itu, ia mulai membantu penelitian Georg Eberhard Rumphius, seorang ilmuwan botani yang karyanya baru dipublikasikan setelah wafat. Chastelein dipercaya untuk menjalankan wasiat Rumphius, memastikan karya-karyanya dalam zoologi, botani, geografi, dan sejarah tidak hilang begitu saja.
Meskipun kariernya terus menanjak, Chastelein merasa semakin tidak nyaman dengan kebijakan VOC yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai bentuk protes, ia membeli tanah di Srengseng (yang kini dikenal sebagai Lenteng Agung) pada tahun 1695 dan menulis buku berjudul “Invallende Gedagaten” (Buah Pikiran) yang mengkritik VOC. Dalam pikirannya, ia menegaskan bahwa tujuan kolonisasi seharusnya bukanlah penindasan, tetapi membangun komunitas yang beradab dan memanusiakan. Ia mengusung gagasan bahwa perdagangan dan kolonisasi harus selaras dengan ajaran Injil, membawa pencerahan serta kesejahteraan bagi semua pihak, bukan sekadar alat eksploitasi.
Banyak orang menyebut Chastelein sebagai seorang misionaris Kristen, tetapi sesungguhnya ia memiliki ambisi lebih besar dari hal itu. Dia adalah seorang saintis yang bersahabat dengan gubernur jenderal VOC sebelum van Outhoorn, yaitu Johannes Camphuys, yang juga memiliki minat dalam ilmu pengetahuan. Dia menulis kritiknya dengan cara yang sangat beradab, bahkan untuk standar zamannya.
Mengembangkan Depok
Setelah keluar dari VOC, Cornelis Chastelein bisa dikatakan sebagai warga tanpa pekerjaan dan jabatan. Ia kemudian mencurahkan waktunya untuk mengelola tanah yang dibelinya pada tahun 1696 dari Lucas van der Meur. Di atas lahan subur yang dialiri sungai, ia membangun perkebunan lada, kebun buah, dan sawah, dibantu oleh budak-budak yang sebagian besar berasal dari Bali dan Makassar.
Chastelein yakin bahwa pertanian adalah kunci bagi kemakmuran komunitasnya. Ia mengembangkan Depok sebagai model masyarakat agraris yang mandiri. Wilayah ini mencakup Mampang, Depok, dan Karang Anyar (Cinere), yang kemudian berkembang menjadi komunitas pertanian yang ideal. Namun, lebih dari sekadar pertanian, Chastelein juga menanamkan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme. Ia tidak memaksa budak-budaknya yang beragama Islam untuk berpindah keyakinan, dan setelah mereka dibebaskan (mardijkers), ia memastikan mereka memiliki hak yang sama.
Pemerintahan otonom yang ia bangun bertahan lebih lama daripada pemerintahan kolonial Belanda. Baru antara tahun 1949–1952, Depok diambil alih oleh Republik Indonesia. Namun, ironisnya, sejarah panjang ini sering dilupakan oleh warganya sendiri. Alih-alih menghargai warisan Chastelein, masyarakat lebih banyak mengenang Depok sebagai kota otonom tanpa melihat akar sejarahnya. Sentimen kolonialisme membuat banyak orang enggan mengakui kontribusi Chastelein. Padahal Chastelein justru menentang eksploitasi dan rasisme yang menjadi ciri kolonialisme saat itu.
Hari ini, Depok sering dianggap sebagai kota tanpa prestasi, padahal sejarahnya begitu kaya. Pondok Cina, salah satu kampung tertua, menyimpan jejak peradaban yang luar biasa. Namun, ironisnya, bangunan-bangunan bersejarahnya kian terancam oleh pembangunan modern. Lambang Kota Depok, berupa buku dan pena, seharusnya menjadi pengingat bahwa kota ini menghargai pemikiran dan perenungan. Sayangnya, maknanya perlahan memudar.
Chastelein adalah sosok yang melampaui zamannya. Ia merintis gagasan tentang hutan kota, kesetaraan, dan pembebasan budak. Namun, warisan pemikirannya banyak dilupakan di masa Depok modern. Jika ingin membangun masa depan yang lebih baik, kita harus kembali belajar dari sejarah.
Pada 28 Juni 1714, Chastelein mengembuskan napas terakhirnya saat matahari mulai condong di ufuk barat. Ia meninggalkan surat wasiat yang membebaskan 150 budaknya beserta keturunan mereka. Dalam wasiatnya ia mewariskan perkebunannya di Depok untuk diurus oleh mantan budaknya. Cornelis Chastelein telah pergi, tetapi jejaknya tetap ada—di sungai yang mengalir, di tanah yang ia bangun, dan di kisah yang menunggu untuk kembali diceritakan.(pp)