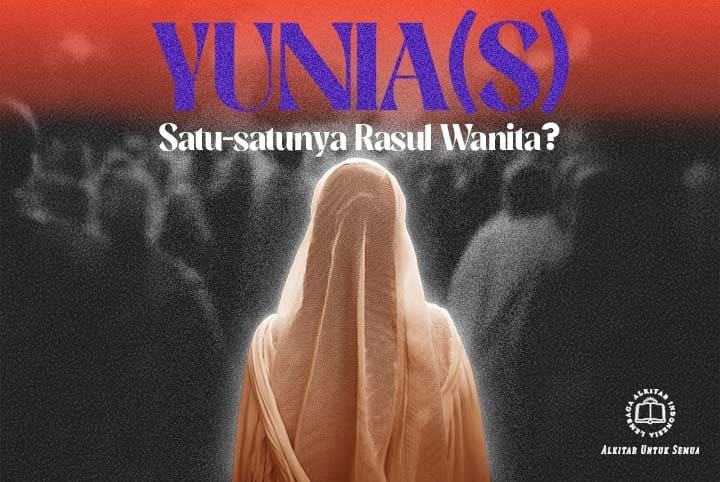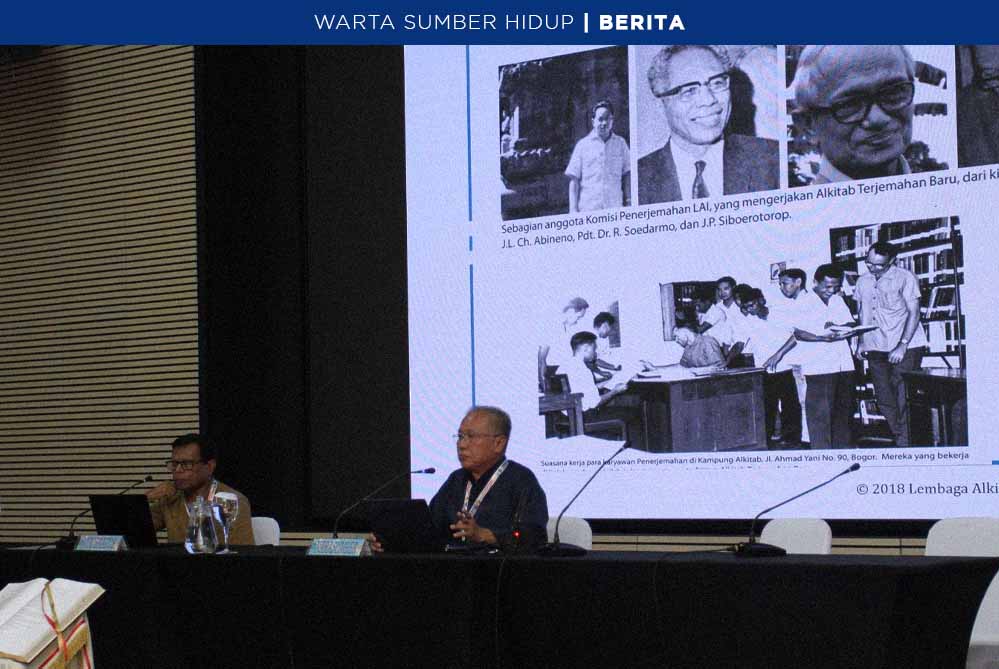Tetapi, carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah rupanya tugas hidup kita. Tapi kita justru mencari yang lain, dan rupanya tidak menemukan. Sejak malam itu Nekhlyudov memulai hidup yang baru sama sekali. (Kebangkitan, hal. 566)
Demikian penutup novel Kebangkitan (1899) karya sastrawan besar Rusia, Lev Nikolayevich Tolstoy atau Leo Tolstoy. Sejak pertobatannya, Tolstoy demikian terinspirasi ajaran Tuhan Yesus dan sering sekali mengutip ayat-ayat Injil dalam setiap tulisan atau novel-novelnya.
Dua novelnya yang lain War and Peace (Perang dan Damai, 1869) dan Anna Karenina (1877) dianggap sebagai dua mahakarya sastra dunia. Tolstoy dipandang sebagai salah satu pengarang terbesar di dunia bukan hanya karena ia kemampuan menulisnya yang menawan, tetap karena ia menulis untuk menyelami jiwa manusia dan menunjukkan jalan menuju kebenaran dan kehidupan yang bermakna. Ia adalah gabungan seniman, filsuf, nabi dan reformator, yang menjadikan sastra bukan hanya sekadar hiburan, melain cermin bagi jiwa dan cahaya bagi hati. “Art is not a handicraft, it is the transmission of feeling the artist has experienced,” demikian tulis Leo Tolstoy.
Masa Kecil dan Remaja
Tolstoy lahir pada 9 September 1828 dalam keluarga bangsawan Rusia. Ayahnya Nikolai Ilyich Tolstoy dan ibunya Maria Nikolayevma Volkonskaya. Pada masa itu seorang bangsawan mempunyai hak-hak istimewa melebihi warga negara biasa. Tolstoy tinggal di sebuah wisma besar dengan tanah luas yang terdiri atas hutan dan lahan pertanian. Wisma dan tanah sekitarnya itu bernama Yasnaya Polyana (Hutan Terang).
Tolstoy baru berusia dua tahun ketika ibunya meninggal. Tujuh tahun kemudian ayahnya meninggal. Lalu ia diasuh oleh neneknya, namun baru saja setahun, neneknya meninggal. Sejak itu, ia dibesarkan oleh bibi-bibinya. Ia tidak kekurangan cinta kasih, namun tanpa sosok ibu, hidupnya terasa kosong. Tulisnya,”Aku berusaha menampilkan tentang ibuku, namun tidak bisa. Sedih rasanya, aku tidak bisa membayangkan wajah ibuku sendiri.”
Pada bagian lain ia mengenang ibunya sebagai sosok yang lembut dan spiritual, meskipun ingatannya samar. Dalam catatan hariannya ia menulis,”Saya tidak ingat suara ibuku, tapi saya yakin ia mencintai saya dengan tulus. Kehilangan itu tetap tinggal di hati saya seperti lubang gelap yang tidak bisa ditambal.”
Tolstoy sangat cerdas, namun ia tidak betah duduk di kelas. Tulisnya,”Seluruh bahan pelajaran oleh guru selama dua jam bisa aku lahap dalam sepuluh menit jika buku itu aku baca sendiri.” Pada usia remaja, ia sudah membaca buku-buku filsafat karangan filsuf Perancis Jean Jacques Rousseau.
Meskipun Tolstoy lebih senang belajar sendiri, ia masuk Universitas Kazan pada 1844. Ia belajar hukum, namun lebih tertarik pada bahasa-bahasa asing dan sastra. Tolstoy tidak terlalu menyukai pendidikan formal. Ia menganggap sistem pengajaran pada masa itu tidak menyentuh inti dan arti kehidupan.
Dalam sebuah surat kepada saudaranya ia menulis,” Aku datang untuk mencari pengetahuan, tapi aku malah disodori hafalan dan rutinitas. Aku ingin memahami hidup, bukan hanya menghafal nama-nama hukum Romawi.”
Ia pun meninggalkan universitas tanpa menyelesaikan gelar, dan kembali ke Yasnaya Polyana. Di sana ia mulai menyusun catatan-catatan pribadi tentang kehidupan, moral, dan keinginan untuk menjadi lebih baik.
Novel-novel awalnya, “Chilhood”, ”Boyhood”, dan ”Youth” bersifat autobiografis. Lewat karya-karya masa mudanya ini kita dapat melihat pergulatan batinnya sebagai seorang muda: antara hasrat duniawi dan kerinduan spiritual, antara keberanian bangsawan dan kerendahan hati seorang murid Kristus sejati.
Pada salah satu catatannya Tolstoy menulis:
“Hari ini aku bangun siang. Aku makan terlalu banyak. Aku berbicara terlalu banyak. Aku tidak membaca Alkitab. Aku tidak menolong siapa pun. Besok aku harus hidup lebih baik.”
Kecenderungan untuk melakukan refleksi diri kelak membentuk gaya khas tulisan-tulisan Tolstoy: narasi yang jujur, telanjang, dan penuh pertanyaan etis.
Meski secara batin ia haus akan kehidupan yang murni dan bermoral, pernah juga Tolstoy muda mengikuti arus dalam gaya hidup bangsawan Rusia: pesta, alkohol, judi dan hubungan asmara. “Aku terjerumus dalam kehidupan penuh dosa…minum, berjudi dan berhubungan dengan perempuan hanya untuk mengisi kekosongan hatiku,”tulisnya.
Saat tinggal d Moskow dan St. Petersburg, Tolstoy bergaul dengan bangsawan-bangsawan muda. Ia terbiasa berjudi dan sering kalah dalam jumlah besar. Demi membayar hutang judinya ia menjual barang-barang berharga dan menyewakan properti miliknya. Namun, setiap kali terpuruk, muncul semangat untuk hidup lebih bersih dan bermakna.
Dalam jurnal pada 1855, ia menulis penyesalan lainnya:
“Aku telah mencicipi segalanya, kesenangan, dosa dan kehormatan. Tapi semuanya tidak menyelamatkan aku dari kehampaan. Aku mencari sesuatu yang abadi.”
Meski mengalami berbagai konflik batin, Tolstoy meyakini bahwa ada tangan Tuhan yang membentuknya melalui berbagai pengalaman hidup. Tulisnya:
“Saya bukan seperti mereka yang tahu pasti siapa dirinya sejak kecil. Saya adalah tanah liat yang terus dibentuk oleh tangan-tangan tak terlihat: kehilangan, cinta, dosa, dan penyesalan.”
Terlibat sebagai sukarelawan militer
Pada 1851, Tolstoy mendaftarkan diri sebagai tentara sukarelawan dan bergabung dengan saudaranya menjadi perwira militer di Kauskasus. Ia berharap pengasingan dari kota akan membantunya hidup lebih bersih. Sebagai sukarelawan militer, Tolstoy mulai mencatat pengamatannya terhadap kehidupan militer, masyarakat lokal dan kematian.
Pengalaman ini kemudian ia tuangkan dalam cerita “The Cossacks” (1852) dan “Sevastopol Sketches” (1855–56), yang ditulis saat ia menjadi tentara dalam Perang Krimea. Di garis depan pertempuran, ia melihat langsung penderitaan manusia dan absurditas perang. Ia mencatat:
“Kita membunuh karena diperintah. Kita mati demi kata-kata yang bahkan tidak kita mengerti. Ini adalah kegilaan manusia.”
Meski masih muda, gaya tulisan Tolstoy mencerminkan kedalaman moral dan observasi tajam. Ia tidak hanya menggambarkan perang sebagai latar cerita, tetapi juga sebagai simbol konflik batin antara kebenaran dan kekuasaan.
Tulisan-tulisannya mulai dikenal dan mendapat pujian. Namun di balik sukses itu, Tolstoy justru merasa semakin terasing dari jati dirinya. Ia mulai mengembangkan pandangan bahwa sastra harus memiliki nilai moral dan tujuan kemanusiaan.
“Aku menulis bukan untuk pujian, tapi untuk menyampaikan kebenaran yang aku temukan…Meski belum sempurna, aku akan terus berusaha mencarinya.”
Menikah dan Mengalami Pertobatan
Pada usia 34 tahun, Tolstoy menikah dengan Sofya Bers, sekretarisnya yang baru berusia 18 tahun. Sofya adalah putri seorang dokter dari kalangan kaum bangsawan. Tolstoy dan Sofya mempunyai 13 orang anak.
Meski sukses sebagai penulis di usia muda, Tolstoy merasa hidupnya kosong. Ia pernah menulis dalam catatan pribadinya bahwa setelah mencapai puncak ketenaran dengan karya agungnya “War and Peace” (1869) dan “Anna Karenina” (1877), ia mengalami krisis eksistensial. “Untuk apa semua ini? Mengapa aku hidup? Mengapa aku menulis?” tanyanya dalam sebuah renungan yang jujur. Ketenaran dan kekayaan tidak bisa mengenyangkan jiwanya yang lapar akan makna.
Di sinilah terjadi titik balik. Tolstoy mulai membaca ulang Injil—bukan sebagai ritual agama, tetapi sebagai pencarian hidup yang sejati. Ia sangat tersentuh oleh Khotbah di Bukit dalam Injil Matius, khususnya kata-kata Yesus: “Kasihilah musuhmu… Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan.” Baginya, inilah inti ajaran Kristus—ajaran cinta kasih yang radikal, non-kekerasan, pengampunan tanpa batas, dan penolakan terhadap segala bentuk dominasi kekuasaan.
Tolstoy menulis:
“Saya menemukan bahwa iman saya pada Kristus hanya benar bila saya mengikutinya… bukan sebagai tuan agama, tetapi sebagai Guru yang Hidup.”
Setelah pertobatan spiritualnya, Tolstoy meninggalkan gaya hidup bangsawan. Ia berpakaian sederhana, mengerjakan ladang bersama petani, memilih menjadi vegetarian, dan tidak mau memiliki properti berlebih. Ia juga mengkritik keras Gereja Ortodoks Rusi yang menurutnya telah menyimpang dari ajaran Yesus yang sejati. Pimpinan gereja disebutnya hanya diam melihat ketidakadilan di tengah masyarakat. Ia menolak dogma, ritualisme, bahkan keikutsertaan gereja dalam pembenaran perang dan kekuasaan. Kritikan-kritikan Tolstoy membuat marah Gereja Ortodoks. Yang makin membuat pimpinan gereja tersinggung adalah, anjuran Tolstoy agar umat berhubungan langsung dengan Tuhan, dari hati ke hati, tanpa harus melalui perantaraan gereja.
Gereja tidak menyukai buku-buku Tolstoy dan kemudian secara resmi mengucilkan (ekskomunikasi) Tolstoy dari gereja. Ia dinyatakan sebagai pengajar sesat.
Tolstoy juga mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah Rusia. Sebagai bagian dari pertobatannya, Tolstoy menolak kekerasan dalam bentuk apa pun. Ia menentang hukuman mati, peperangan dan wajib militer. Ia dengan teguh menyatakan kekerasan adalah penyangkalan terhadap ajaran Kristus. Pemerintah juga sebenarnya tidak menyukai Tolstoy, namun ragu-ragu menangkapnya karena statusnya sebagai bangsawan.
Pengucilan Tolstoy dari Gereja akhirnya hanya merendahkan kewibawaan Sinode sendiri dan mengangkat popularitas Tolstoy. Popularitas Tolstoy makin lama makin besar, bahkan hingga mancanegara, sehingga timbul perumpamaan bahwa di Rusia ada dua raja, yang satu di St. Petersburg, di bukota negara, di Istana Zimnyii, dan yang kedua di Yasnaya Polyana, di dekat kota Tula. Inilah tanah kepunyaan Leo Tolstoy.
Para pengagum Tolstoy berasal dari berbagai negara. Surat-surat pembaca datang dari seluruh dunia, antara lain dari Mahatma Gandhi. Ketika itu Gandhi masih menjadi pengacara di Afrika Selatan dan nantinya menjadi Bapak Pendiri Bangsa India. Gandhi menyebut buku karya Tolstoy The Kingdom is Within You (Kerajaan Allah Ada di Dalam Kamu)telah mengubah hidupnya dan memberinya keyakinan untuk memperjuangkan kebenaran secara damai. Gandhi kemudian terus bersurat-menyurat dengan Tolstoy dan banyak mempelajari Injil dari Tolstoy. Diilhami oleh Tolstoy, Gandhi menerapkan prinsip anti kekerasan atau ahimsa dalam revolusi kemerdekaan India.
Memilih Hidup Sederhana
Dalam masa-masa akhir hidupnya, Tolstoy meninggalkan hak-hak atas karya-karyanya. Ia menolak royalty dan meminta agar karyanya menjadi milik publik. Ia mendirikan sekolah untuk petani, menulis buku bacaan untuk anak-anak, dan terus menulis surat-surat nasihat moral kepada siapa pun yang memintanya. Ia ingin hidupnya menjadi cermin ajaran yang ia yakini.
Tuturnya dalam The Kingdom is Within You, ” Gereja berkata: aku milik Kristus. Tapi Kristus berkata: Aku milik mereka yang miskin, lapar, dan haus akan kebenaran.”
Kerajaan Allah bagi Tolstoy bukanlah tempat fisik, bukan pula institusi. Itu adalah kerajaan batin, di mana hati manusia tunduk kepada kasih, kejujuran dan belas kasih.
Tetapi, carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. (Matius 6:33). Ayat ini menjadi semacam inspirasi hidup baru bagi Tolstoy. Ia percaya bahwa perubahan dunia bukan dimulai dari revolusi politik, tetapi dari transformasi batin manusia.
Dalam ketaatannya kepada Kristus, Tolstoy membagi tanah miliknya yang sangat luas kepada para petani miskin. Ia menanggalkan semua keistimewaannya sebagai bangsawan, lalu hidup dengan sangat sederhana sebagai petani dan tukang sepatu. Sementara itu ia terus menulis.
Melihat perilaku Tolstoy yang sangat eksentrik itu, istrinya sering kesal dan marah-marah. Ia menganggap Tolstoy sinting. Pada suatu hari Tolstoy tidak tahan lagi mendengar omelan istrinya. Lalu di tengah salju yang dingin membeku ia diam-diam pergi dari rumah dan menumpang kereta api. Di tengah perjalanan kakek bungkuk berusia 82 tahun itu mengalami masuk angina, jatuh sakit dan mengembuskan napas penghabisan di stasiun kecil Astapovo. Peti matinya diiringkan ke tempat peristirahatan terakhir di Yasnaya Polyana oleh puluhan ribu orang dari segala pelosok yang memberikan penghormatan terakhir kepada sastrawan agung, yang dikebumikan tanpa upacara gerejawi. Ia dimakamkan di tengah hutan, di bawah pohon rindang, tempat favoritnya sedari kecil. Tolstoy meninggal dalam damai, seperti seseorang yang telah menapaki perjalanan panjang dan akhirnya pulang.
Tidak banyak gereja mengenal dan menghargai Leo Tolstoy. Ia adalah contoh bagaimana Allah dapat bekerja melalui suara-suara di luar institusi gereja untuk mengingatkan kembali dunia akan pesan Kristus yang memerdekakan. Leo Tolstoy memberi kita teladan perjuangan rohani yang jujur dari seorang manusia yang dengan serius mencari Kerajaan Allah dan kebenarannya, serta mengajak dunia untuk hidup seturut Injil.
Dalam dunia yang dikuasai oleh kekerasan, penindasan dan keserakahan, Tolstoy meyakini masih ada jalan yang lain. Tulisnya: “Jalan menuju Kerajaan Allah bukanlah jalan kemenangan duniawi, tetapi jalan kerendahan hati, pengampunan dan cinta yang tidak menuntut balas.” Tolstoy akan selalu diingat bukan hanya pewarta ajaran Kristus, tetapi sebagai pelayan-Nya yang menghidupi ajaran Sang Guru setiap hari.